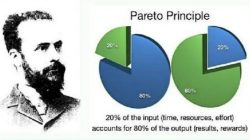Secara khusus, masyarakat tradisional di Tapanuli Selatan meyakini bahwa ketika nilai-nilai adat ditinggalkan, atau ketika maksiat merajalela, maka keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur menjadi terganggu.
Dalam situasi seperti itu, alam dipercaya akan ‘berbicara’. Salah satu bentuknya harimau muncul dari hutan, bukan untuk memangsa, melainkan memberi tanda bahwa sesuatu sudah melampaui batas.
Pandangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir spiritual masyarakat adat, di mana hubungan manusia dengan lingkungan bukan semata bersifat fisik, melainkan juga metafisis. Apa yang tampak di alam bisa mencerminkan kondisi moral masyarakat.
Antara Kearifan Lokal dan Fakta Ekologis
Dari sisi ekologi, penampakan harimau memang sering berkaitan dengan berkurangnya habitat alami, perambahan hutan, dan konflik ruang antara manusia dan satwa liar.
Data dari Forum HarimauKita menyebutkan bahwa populasi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang tersisa saat ini hanya sekitar 600 ekor di alam liar, menjadikannya sangat rentan terhadap gangguan habitat.
Jika hutan di sekitar kita mengalami penyusutan atau gangguan, maka besar kemungkinan harimau turun mendekati permukiman.
Namun yang menarik, meski penjelasan ekologis tersedia, pandangan adat tak lantas pudar. Bahkan, dalam banyak kasus, kepercayaan adat justru memperkuat upaya konservasi.
Sebab, ketika harimau dianggap sebagai jelmaan leluhur atau penjaga alam, maka masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam memperlakukan hutan dan satwa.
Maka dari itu, peristiwa di Desa Pudun Jae bisa dilihat dari dua sudut. Pertama, sebagai peringatan ekologis bahwa habitat satwa mulai terdesak dan butuh perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pegiat lingkungan.