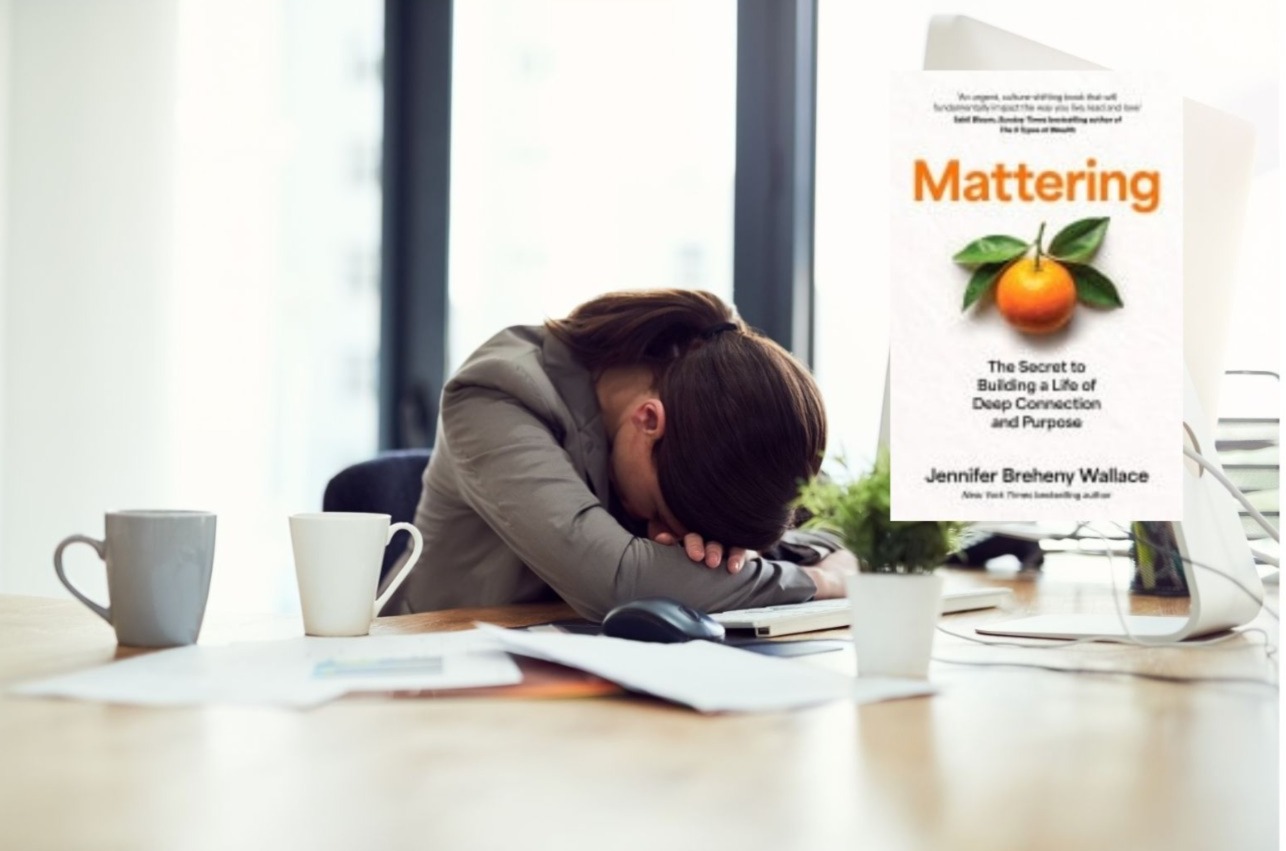LENSAKINI – Di tengah dunia yang bergerak cepat dan bising oleh tuntutan produktivitas, banyak orang menjalani hari dengan satu perasaan yang sulit dijelaskan tetapi sangat nyata merasa tak dibutuhkan. Pekerjaan selesai, target tercapai, tanggung jawab dijalankan.
Namun ketika malam tiba, ada kehampaan yang tidak terisi oleh pencapaian apa pun. Inilah akar sunyi dari krisis mental modern yang sering luput dibicarakan.
Selama ini, kesehatan mental kerap dikaitkan dengan stres kerja, tekanan ekonomi, atau derasnya arus teknologi. Semua itu benar, tetapi belum menyentuh lapisan terdalam.
Banyak orang tidak runtuh karena terlalu banyak beban, melainkan karena merasa tidak berarti bagi siapa pun. Tidak dicari, tidak diingat, tidak benar-benar dilihat sebagai manusia yang punya nilai.
Fenomena ini muncul di berbagai ruang kehidupan. Seorang pekerja rajin datang paling awal dan pulang paling akhir, tetapi namanya jarang disebut.
Seorang pengasuh merawat anggota keluarga tanpa keluhan, namun keberadaannya dianggap sebagai kewajiban, bukan pengorbanan. Seorang pensiunan kehilangan rutinitas dan identitas karena tidak lagi memiliki peran sosial yang jelas. Bahkan di tengah keramaian, seseorang bisa merasa sendirian ketika kehadirannya tidak memberi dampak bagi siapa pun.
Jennifer Breheny Wallace menyebut kondisi ini sebagai krisis mattering. Mattering adalah perasaan bahwa diri kita dihargai dan sekaligus memiliki sesuatu yang bernilai untuk diberikan. Bukan sekadar diakui secara formal, tetapi dirasakan secara nyata dalam relasi sehari-hari.
Ketika seseorang merasa mattering, hidup terasa punya bobot. Ada alasan untuk bangun pagi, ada makna di balik usaha, ada keyakinan bahwa keberadaan diri membawa pengaruh bagi orang lain.